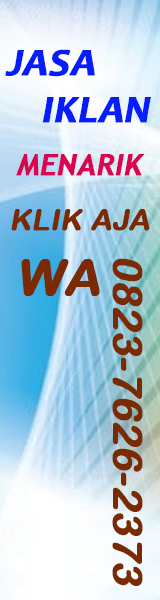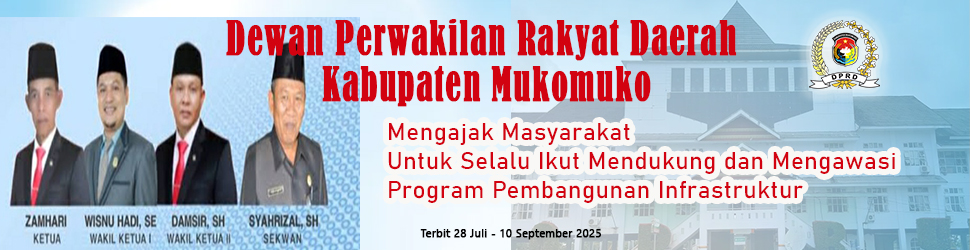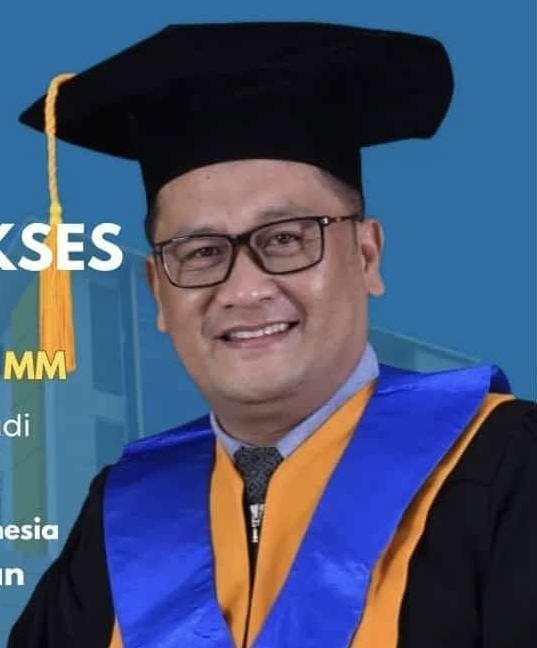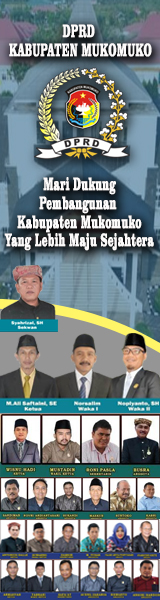BENGKULU – Wacana penggantian julukan Provinsi Bengkulu dari “Bumi Rafflesia” menjadi “Bumi Merah Putih” sedang mengemuka dan memancing respons publik yang beragam. Di satu sisi, langkah ini tampak sebagai bentuk afirmasi nasionalisme, sebuah upaya menyelaraskan identitas lokal dengan simbol-simbol kebangsaan yang luhur. Di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah perubahan ini benar-benar mencerminkan identitas, sejarah, dan aspirasi kolektif masyarakat Bengkulu?
Julukan “Bumi Rafflesia” bukan sekadar metafora floristik yang bersifat kosmetik. Ia adalah simbol geografis, ekologis, sekaligus historis. Rafflesia arnoldii, bunga langka berukuran raksasa yang hanya mekar di hutan tropis tertentu, menjadi ikon kebanggaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dalam konteks manajemen merek daerah (place branding), simbol ini mencerminkan resource-based identity, yakni identitas yang bersumber dari kekayaan alam yang unik, langka, dan otentik. Dengan begitu, ia bukan hanya penanda estetis, tetapi representasi dari diferensiasi simbolik Bengkulu di antara provinsi lain.
Menghapus simbol ini tanpa kajian mendalam berisiko melemahkan ekuitas brand Bengkulu yang telah dibangun selama puluhan tahun melalui promosi wisata alam, konservasi lingkungan, hingga literatur budaya. Dalam era ekonomi berbasis narasi dan pengalaman, simbol daerah tidak bisa diperlakukan sebagai atribut yang bisa diganti semaunya. Ia memuat nilai-nilai historis, naratif, dan emosional yang menyatu dalam kesadaran kolektif masyarakat.
Simbol merupakan “sistem makna” yang menjembatani antara realitas sosial dan identitas budaya. Dalam masyarakat Bengkulu, terdapat filosofi hidup yang dikenal dengan tahan pade, yakni nilai kesabaran, keuletan, dan loyalitas untuk menjaga apa yang telah diwariskan, bahkan di bawah tekanan dan keterbatasan. Rafflesia, yang hanya mekar dalam kondisi ekologis tertentu, melambangkan nilai ini: langka, penuh tantangan, tetapi bernilai tinggi. Menggantinya dengan simbol nasional seperti bendera Merah Putih tanpa proses pemaknaan ulang berisiko dianggap sebagai langkah tergesa, bahkan ahistoris, yang justru mengaburkan kearifan lokal.
Dalam ranah sosial-politik Bengkulu, dikenal pula falsafah sakato yang bermakna permufakatan dalam pengambilan keputusan. Nilai ini telah menjadi fondasi dalam adat dan tata kehidupan sosial masyarakat. Sehingga setiap upaya mengganti simbol identitas daerah seyogianya melalui proses dialog yang partisipatif, deliberatif, dan terbuka. Bukan sekadar keputusan top-down yang minim transparansi dan akuntabilitas. Identitas daerah bukanlah milik eksklusif elit politik, melainkan milik bersama yang harus disepakati bersama pula.
Bendera Merah Putih, tentu merupakan simbol nasional yang sakral, yang wajib dijunjung setinggi-tingginya. Namun, identitas daerah tidak lahir dalam ruang hampa sejarah. Bengkulu memiliki jejak panjang dalam narasi kebangsaan. Di sinilah Bung Karno diasingkan oleh Belanda dan menjalani masa-masa kontemplatif yang membentuk visi politiknya. Di Bengkulu pula lahir Fatmawati, ibu negara pertama yang menjahit Sang Saka Merah Putih dengan tangannya sendiri—sebuah kontribusi simbolik dan nyata bagi republik ini. Menghapus julukan “Bumi Rafflesia” tanpa menautkan sejarah ini justru berpotensi mereduksi makna nasionalisme itu sendiri.
Sebagai wilayah dengan kekayaan sejarah dan ekologi yang khas, Bengkulu justru berpeluang memadukan antara identitas lokal dan semangat nasional secara sinergis. Dalam kerangka manajemen strategis, simbol nasional saja tidak cukup membangun diferensiasi dalam peta kompetisi antarwilayah. Daya saing daerah ditentukan oleh kekhasan yang tidak bisa diduplikasi. Keunggulan kompetitif berkelanjutan hanya bisa dibangun dari sumber daya yang langka, otentik, dan sulit digantikan. Rafflesia memenuhi semua syarat tersebut.
Rafflesia bukan bunga biasa. Ia bukan sekadar daya tarik visual, tetapi metafora dari kekayaan ekologis, ketahanan sosial, dan filosofi hidup masyarakat. Ia menjadi simbol yang menumbuhkan rasa bangga, memantik rasa memiliki, dan menggerakkan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan dan identitas. Dalam konteks pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengembangan UMKM berbasis lokalitas, simbol seperti ini memberikan kekuatan promosi yang berkelanjutan. Ia bisa menjadi tulang punggung narasi destinasi, bahan baku kreatif produk lokal, hingga jembatan edukasi untuk generasi muda.
Yang tidak kalah penting, simbol Rafflesia merupakan jembatan antara sejarah, nilai, dan arah masa depan. Mengutip filsuf Paul Ricoeur, identitas bukanlah sesuatu yang beku dan statis, melainkan narasi yang terus ditulis ulang, diolah, dan dipertanyakan. Dalam kerangka ini, simbol adalah medium yang mengikat masyarakat dalam satu cerita kolektif lintas generasi. Jika simbol ini dihapus atau digantikan tanpa makna baru yang setara, maka yang hilang bukan hanya nama, melainkan kesinambungan identitas dan arah pembangunan.
Alih-alih mengganti, barangkali yang lebih kita butuhkan adalah menafsir ulang. Rafflesia tetap bisa menjadi simbol ekologis yang kuat sekaligus manifestasi filosofi nilai. Kita pun tetap bisa mengibarkan semangat merah putih melalui kerja nyata, partisipasi aktif, dan pembelaan terhadap keadilan sosial. Simbol lokal dan nasional seharusnya tidak dipertentangkan, karena keduanya lahir dari semangat yang sama: cinta tanah air. Yang satu mengakar di bumi, yang lain menjulang ke langit.
Oleh: Assoc. Prof. Dr. Marwan Effendi, S.E., M.M., CPRM
Ketua Program Pascasarjana STIE Manajemen Bisnis Indonesia Depok – Jawa Barat;
Peneliti Bencoolen Institute Bengkulu;
Mahasiswa Magister Aqidah Filsafat Islam STIA SADRA Jakarta